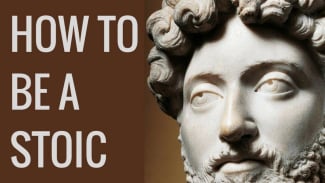Terjebak Pandangan Orang: Media Sosial dan Perangkap Scopophilic
- Tracy Le Blank/ Pexel
NTT ViVa– Di tengah gemuruh dunia digital yang kian bising, manusia modern berjalan dalam kerumunan yang tak kasat mata. Ia menatap layar, tetapi sesungguhnya sedang menatap dirinya sendiri—melalui mata orang lain. Ia mengabadikan momen, bukan untuk mengenangnya, tapi untuk memastikan bahwa dunia tahu ia hidup, eksis, dan (semoga) dikagumi. Ini bukan lagi sekadar tentang membagi cerita. Ini adalah tentang dipandang. Disaksikan. Diinginkan. Di tengah riuhnya media sosial, manusia terjebak dalam apa yang disebut perangkap scopophilic.
Scopophilia: Ketika Pandangan Menjadi Hasrat
Scopophilia, sebuah istilah dari psikoanalisis yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud dan kemudian berkembang dalam kajian film dan media oleh Laura Mulvey, merujuk pada kenikmatan yang diperoleh dari melihat dan dilihat. Dalam konteks media sosial, kita bisa melihatnya sebagai sebuah mekanisme psikologis: kita menikmati menonton kehidupan orang lain, dan sekaligus mendambakan untuk ditonton.
Dulu, dunia panggung dan layar kaca hanya dimiliki oleh para aktor dan aktris. Tapi kini, semua orang punya panggungnya sendiri—dalam bentuk Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Twitter. Yang berubah bukan hanya teknologinya, tetapi juga struktur psikis kita. Jika dahulu kita menonton televisi sebagai hiburan, kini kita membuat diri kita sendiri menjadi tontonan.
Narasi Kehidupan yang Dipertontonkan
Aldi, seorang pemuda dari pinggiran kota, setiap hari memulai harinya dengan mengambil foto kopi paginya, menambahkan filter hangat, dan menuliskan caption puitis: "Secangkir harapan di tengah realita yang pahit." Di balik layar, ia sedang berjuang dengan kecemasan, tekanan pekerjaan, dan relasi yang rapuh. Tapi siapa yang peduli pada kenyataan jika ilusi lebih indah?
Di media sosial, kita tidak sekadar membagikan apa yang kita lakukan. Kita menciptakan versi terbaik dari diri kita. Kita edit wajah kita, kita filter emosi kita, kita kurasi potongan hidup yang “layak dipamerkan”. Dan pada akhirnya, kita hidup dalam realitas yang dikonstruksi, bukan yang sebenarnya.